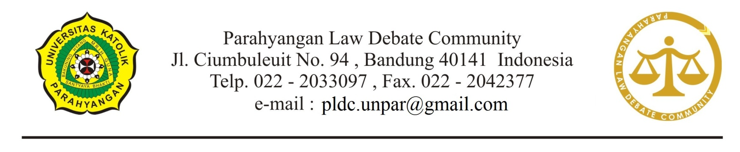oleh: Martin Setiawan Tjahjadi
Setelah melewati kontemplasi panjang selama kurang lebih 110 tahun lamanya, akhirnya kini perempuan Bali berhak untuk memperoleh harta warisan! Mengapa tidak? Dengan adanya Pasamuhan (pertemuan) Agung III Majelis Utama Desa Pekramen Bali tertanggal 15 Oktober 2010, kini para perempuan Bali bisa bernapas lega, pasalnya perjuangan mereka untuk memperoleh kesetaraan gender dari segi lapangan hukum waris adat mereka sudah mencapai titik kulminasinya. Putusan MUDP Bali itu memang cukup mencengangkan sekaligus memberikan rona kebahagiaan bagi sekiranya hampir seluruh perempuan Bali, karena kini mereka berhak untuk mendapatkan harta warisan setelah sebelumnya perempuan Bali tidak berhak mewaris lantaran sistem pewarisan di Bali menganut sistem patrilineal/ kebapaan. Bukan hanya itu, jika perceraian terjadi, perempuan Bali pun berhak memperoleh hak asuh anak setelah sebelumnya hak asuh anak harus jatuh ke tangan pihak bapa (kapurusa/ purusa). Dahulu kala pemandangan seperti ini mungkin adalah sesuatu hal yang diutopiakan oleh beberapa pihak, bahkan cenderung dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu. Bagaimana mungkin sistem pewarisan adat yang sudah terpatri (adat nan teradat) sejak tahun 1900-an itu bisa 'diruyak' dalam era sekarang ini?
Menelisik lebih jauh, rasanya masih melekat dalam ingatan laten kita bahwa perubahan serupa namun tak sama pernah terjadi dahulu kala di Bali. Tatkala janda Bali yang kehilangan suaminya harus turut serta membakarkan diri hidup-hidup dalam upacara Ngaben suaminya, menurut persepsi masyarakat adat setempat jaman dulu, tindakan seperti itu merupakan suatu tindakan mulia nan terpuji sebagai bentuk perwujudan dharma tertinggi sang janda terhadap suaminya. Namun pandangan seperti itu menemui titik kontras bagi beberapa pihak yang merasa bahwa tindakan seperti itu dirasakan kurang tepat dilakukan. Pasalnya banyak hal yang bisa dilakukan seorang janda yang ditinggal pergi suaminya, seperti bersama-sama membesarkan anak mereka bersama keluarga suami (purusa) dalam batas-batas tertentu, melanjutkan hak untuk hidup guna memperoleh kehidupan yang lebih baik, dll. Dinamika sosial masyarakat adat Bali sehubungan dengan hal itu pun menemui pembaharuan adat mengingat banyaknya 'gugatan' yang dilayangkan kepada para tetua adat dan/ atau lembaga adat setempat (de gezaghebende). Alhasil untuk menggenapi kebutuhan masyarakat adat sekaligus mengurangi ketegangan sosial, maka tindakan pembakaran janda hidup-hidup menjadi ditiadakan. Alasannya sangat sederhana, yakni karena masyarakat tidak dapat mempertahankan adat tersebut. Di samping kebutuhan masyarakat yang mengkehendakinya, saya kira unsur kebudayaan luar pun sekiranya turut mempengaruhi. Semisal banyak kaum cendekiawan yang berkunjung keluar masuk Pulau Bali dan pada saat yang bersamaan timbul pertukaran konsepsi-esensi tentang nilai-nilai kebenaran universal, terjadi proses akulturasi, bahkan terjadi juga internalisasi nilai akan suatu hal yang dianggap lebih baik sehingga menuntut terjadinya perubahan kebudayaan/ culture change.
Pasamuhan Agung III MUDP 15 Oktober 2010 pun tidak hanya menghasilkan keputusan yang memberikan keadilan hak waris perempuan Bali dan hak asuh saja. Lebih dari itu, putusan MUDP pun melarang diselenggarakannya Ritual Patiwangi. Ritual Patiwangi adalah ritual penanggalan kasta yang harus dilakukan apabila seorang wanita dari kasta tertentu hendak menikah dengan pria tak berkasta. Konsekuensi sosial yang harus diterima adalah bahwa wanita tersebut akan dikucilkan/ didiskriminasikan dalam pergaulan kemasyarakatan pihak ibu (pradana). Bahkan apabila terjadi perceraian, pihak keluarga wanita tidak akan menerima kembali sang anak. Kini Hukum Adat Bali menemui titik pembaharuan, bahwa wanita yang bercerai dapat kembali masuk ke keluarganya dengan status Mulih Daa.
Permasalahan apik yang mendasar sekarang ini adalah mensosialisasikan keberadaan putusan tersebut sebagai langkah fundamental dalam pengaplikasiannya sebagai hukum positif. Namun, bukan hanya itu, seperti yang dikatakan Prof. Satjipto Rahardjo, bahwa Hukum Adat kita sekarang sedang mengalami ramifikasi substansial yang perlu untuk dibenahi. Banyak konsepsi adat mengenai perkawinan yang acap kali memberatkan pihak wanita. Wanita seakan ditempatkan dalam posisi yang dirugikan. Menurut pendapat Prof. Sulistyowati Irianto, hal itu terlihat mulai dari kekerasan domestik yang melegitimasikan perempuan sebagai harta mutlak suami karena mas kawin sudah dibayar, preference marriage/ transaksi politik dan ekonomi dalam hubungan antar keluarga/ trah, dll. Memang dibutuhkan suatu keberanian, kegigihan, dan keniscayaan dalam memperjuangkan kesetaraan gender di negeri kita ini. Mungkinkah langkah berani nan revolusioner MUDP Bali terkait putusan kontroversial mengenai perempuan Bali dan haknya bisa dijadikan acuan oleh masyarakat adat non Bali yang menganut sistem pewarisan patrilineal maupun matrilineal? Hmm... Rasanya pergulatan kebutuhan pembaharuan hukum adat sedang memulai babak baru. Semoga!